Kenapa mesti sendiri? Apa memang aku diciptakan untuk sendiri? Kesendirian telah terlalu mengintimiku. Sejak lahir aku telah sendiri. Tak pernah sekalipun kulihat wajah Ayah dan Ibu. Ayah meninggal beberapa bulan setelah kehamilan ibu. Ibu? Sejak kecil aku telah menjadi pembunuh. Aku telah membunuh ibu dengan ‘melahirkanku’. Di panti asuhan pun aku tetap sendiri. Aku tak mau seorang pun berbicara padaku atau menyentuhku. Hiperbolic memang. Tapi begitulah kenyataannya.
Aku tak mau selamanya hidup dalam kesendirian. Apalagi terisolasi. Sekali terisolasi di kamar mandi, hanya 3 jam. Namun selama itu aku sudah begitu tersiksa. Aku takut sendiri, walau pada kenyataannya aku memang selalu sendiri. Hidupku terisolasi bertahun-tahun ini.
Aku tak tahu apa yang menarik dari anak tak punya kawan sepertiku. Aku tak tahu mengapa Papa dan Mama memilihku menjadi anak angkat mereka. Mengapa bukan anak-anak lain yang lebih cantik, lucu, dan telah bergaya semanis mungkin? Mengapa justru aku? Tapi yang jelas mereka sangat baik padaku. Apapun yang kuinginkan selalu terpenuhi. Sekolah hingga perguruan tinggi yang tak pernah kubayangkan, kini benar-benar nyata.
Akhirnya semua berubah sejak Mama hamil. Itu anak pertama yang lama mereka dambakan. Ya, anak pertama. Bukan anak kedua seperti yang mereka katakan. Karena aku bukan anak Papa dan Mama. Karena aku hanya anak pungut dari panti asuhan. Bukan dari rahim Mama.
Silvia menjadi adik kesayanganku. Dia menyayangiku layaknya kakak kandung sendiri. Memang begitulah yang ia tahu. Mungkin ia tak pernah menyadari, atau justru tak mau menyadari perbedaan mencolok antara kami? Kulitnya kuning sedang aku sawo matang. Dia sipit, aku tidak. Dia berbau Cina, aku berbau Jawa. Apa ia tak pernah merasa aneh? Padahal orang lain saja selalu menanyakannya.
Di keluarga ini aku tak kurang kasih sayang. Semua menyayangiku. Tapi, hanya sendiri yang ada di otakku. Apalagi bila mengingat statusku. Aku akan semakin merasa sendiri. Sayangnya, aku selalu mengingatnya.
“Dasar anak kampung! Nggak tau terimakasih. Udah dijadiin keluarga malah ngelunjak.” Silvia menggerutu di depanku hari itu.
“Kenapa, Dik?” tanyaku padanya. Selama ini hanya Silvia yang dapat membantuku melupakan kesendirianku. Dia obat sendiriku. Karena aku sangat menyayanginya. Sangat!!
“Itu Si Nova. Udah ditolong, dihidupin, eh malah nggak tau terimakasih gitu. Pacar kakaknya diembat juga. Aku kan kasihan lihat Mbak Retno jadi patah hati kayak gitu.” katanya emosional.
“Dasar! Anak angkat aja belagu!”
CRASSHH….
Seperti ada kilat menyambarku tiba-tiba. Aku serasa tertampar. Anak angkat…
Adikku memang manja. Seperti anggapan orang tentang anak terakhir. Kekanak-kanakan, egois, mau menang sendiri, tapi… kadang ia begitu sosialis. Suka merajuk dan agak centil. Aku tak mampu menolak bila ia telah merayuku. Karena aku sangat mencintainya. Tapi, benarkah kata-kata itu keluar dari mulutnya? Begitu rendahkah pandangannya terhadap anak angkat? Apa aku salah jika aku juga seorang anak angkat?
“Sudahlah. Kenapa kamu jadi sewot? Memangnya pacar kamu yang direbut? Lagipula tindakannya itu kan tidak ada hubungannya dengan status dia sebagai anak angkat.” Aku mencoba menanggapi dengan tegar, agar terlihat biasa.
“Tentu saja ada. Kalau dia sadar ama statusnya, dia nggak bakal ngelakuin tindakan semacam itu. Pokoknya sekali anak angkat ya anak angkat. Nggak tau diri!”
Silvia masih terus menggerutu. Dan tanpa berkata apa-apa lagi, aku masuk ke kamar dan mengunci pintu. Aku menangis sepuas-puasnya. Ternyata, semua sudah harga mati untuk Silvia.
Malam itu Papa, Mama dan Silvia duduk di ruang tamu. Dengan sangat hati-hati Papa dan Mama menjelaskan statusku pada Silvia. Mereka menunjukkan kartu keluarga yang selalu rapi ‘disembunyikan’ darinya. Silvia tampak menitikkan airmata. Papa dan Mama meminta maaf karena tak memberitahukan hal itu sejak awal.
“Silvia sayang sama Mbak. Siapapun dia, Silvia sayang dia, Pa. Dia kakakku, Ma.” Semua menangis. Lalu hening.
“Pa, Mbak Shinta…!!” teriak Silvia tiba-tiba. Panik. Seharian aku tak keluar kamar. Silvia tentu teringat makiannya pada Novi di depanku.
Pintu digedor kuat. Tak ada sahutan. Papa mendobraknya.
“SHINTA…!!!”
Aku menangis di sudut kamar. Aku menyesal. Mengapa kuakhiri hidupku begitu cepat? Ternyata mereka sangat tulus mencintaiku. Harusnya aku tahu bahwa Tuhan ada. Menemaniku. Hingga dia memberikan keluarga ini untukku. Ah…terlanjur kuakhiri hidupku.
Yogyakarta, 25 Juli 2005

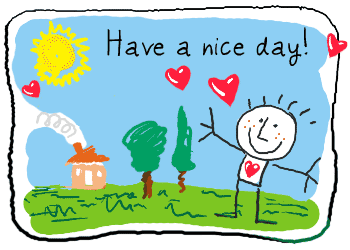
No comments:
Post a Comment